Mengenal Orang Barito Abad XIX
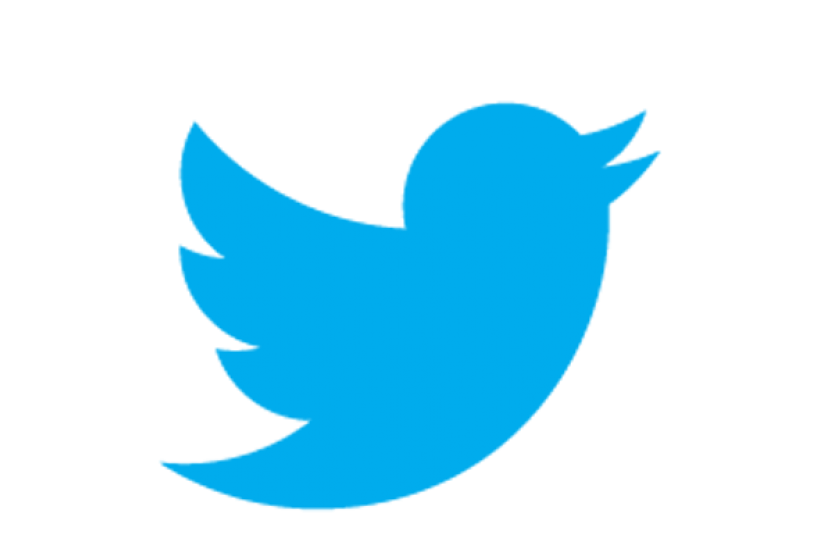
Peresensi: Apai Sesil
Tebal buku sejarah ini 238 halaman. Ditulis oleh Damianus Siyok, mantan jurnalis Majalah Kalimantan Review dan diterbitkan PT. Sinar Begawan Khatulistiwa, Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Juli 2025).
Schwaner menuliskan bahwa penghuni Sungai Barito dari muara hingga hulu adalah: Dayak Ngaju, Maanyan, Lawangan, Dusun, Siang-Murung, dan Punan. Dari catatan ini, pembaca mungkin bertanya: di manakah orang Banjar? Schwaner menulis pada masa eksisnya pemerintahan Sultan Adam, sehingga yang dimaksud dengan “Banjar” pada masa itu adalah Kerajaan Banjar; bukan etnis atau suku.
Pada abad ke-16, orang Ngaju di muara Sungai Barito, di bawah kepemimpinan Patih Masih, Patih Balit, Patih Balandean, Patih Balitung, dan Patih Muhur, mengangkat Pangeran Samudera sebagai raja di kawasan Kuin. Kerajaan baru ini dinamakan Banjarmasih, mengikuti nama kampung yang dipimpin Patih Masih.
Kehadiran kerajaan baru ini menimbulkan peperangan dengan kerajaan Daha di wilayah Nagara. Untuk memperkuat posisinya, Samudera dan kelima Patih Dayak Ngaju meminta bantuan militer dari Sultan Demak. Syarat dari Demak adalah agar raja dan para pembesar Banjar masuk Islam. Syarat ini diterima oleh Pangeran Samudera dan para Patih, maka pada tahun 1526, para pendiri Kerajaan Banjar resmi memeluk Islam di bawah bimbingan penghulu Demak.
Baca juga: https://kalimantanreview.com/nuansa-hijau-hak-asasi-manusia/
Ini adalah kawasan muara Barito. Dalam Hikayat Banjar—sebuah prosa naratif abad ke-17 yang diteliti oleh Prof. Johannes Ras dari Universitas Leiden—disebutkan bahwa saat kerajaan baru berdiri, terdapat dua kelompok di Bandar Masih: orang Negeri (Dayak Ngaju) dan orang Dagang (Melayu, Cina, Bugis, Arab, dan Jawa).
Jumlah orang Negeri diperkirakan sekitar 6.000 jiwa dan orang Dagang 1.000 jiwa. Berdasarkan berbagai perjanjian antara Sultan dan Belanda sejak pemerintahan Pangeran Batu (Sunan Nata Alam), Sultan Sulaiman, dan Sultan Adam, orang-orang Negeri tunduk pada hukum Sultan, sementara orang Dagang tunduk pada hukum Belanda.
Terbentuknya Etnis Banjar
Kerajaan Banjar adalah entitas sosio-politik yang eksis dari abad ke-16 hingga ke-19, sedangkan Etnis Banjar adalah entitas etno-kultural dan etno-religius yang mulai terbentuk pada awal abad ke-20.
Mary Hawkins menjelaskan bahwa identitas Etnis Banjar muncul bersamaan dengan konsep keindonesiaan pada awal abad ke-20, yakni hasil peleburan antara orang Negeri dan orang Dagang. Karena Etnis Banjar terbentuk dari berbagai kelompok dan bangsa—yakni orang Dayak dan pendatang Melayu, Bugis, Arab, serta Jawa yang memeluk Islam, maka fenomena ini dapat dijelaskan dalam kerangka etnogenesis, yaitu pembentukan kelompok etnis baru melalui perpaduan unsur budaya dan politik. Andrew Gillett menyebut etnogenesis sebagai fenomena munculnya kelompok sosial baru yang membentuk identitas kohesif (Gillett 2002, hlm. 244).
Baca juga:
Topik tentang Banjarmasih dan orang Banjar terangkum dalam Bab IV dan Bab VI. Bab VI juga membahas orang Dayak Ngaju di muara Barito, termasuk kelompok Bakumpai.
Di hulu Bandar Masih terdapat Bandar Muara Bahan, kawasan orang Bakumpai—Dayak Ngaju yang mulai memeluk Islam sejak tahun 1526. Schwaner menulis bahwa hampir seluruh orang Bakumpai telah memeluk Islam pada tahun 1688. Pada tahun 1843–1845, mayoritas mereka menjalani aktivitas sebagai pedagang. Jumlah mereka sekitar 5.750 jiwa dan tersebar di Muara Bahan, kawasan Maanyan, Lawangan, Dusun, Siang-Murung, Mahakam, dan Pulau Petak. Oleh karena itu, ciri utama orang Bakumpai adalah Islam, dengan Bahasa Dayak Ngaju yang dipengaruhi unsur Melayu, Cina, dan Arab.
Orang Bakumpai tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan Islam. Di beberapa kawasan Lawangan, Dusun, dan Siang-Murung, mereka bahkan diangkat sebagai kepala suku. Tahun 1857, Bangert mengangkat Damang Marta Djaya dari Bakumpai sebagai Kepala Karau.
Karena pengaruh dagang dan ikut orang Bakumpai masuk islam, tak heran, banyak orang Maanyan, Lawangan, Dusun, dan Siang-Murung menyebut diri mereka telah “jadi Bakumpai” saat memeluk Islam di abad ke-19. Schwaner menuliskan bahwa hal ini mempercepat pertumbuhan populasi Bakumpai.
Sebagai penganut Islam yang taat, identitas Bakumpai berbeda dari Banjar. Jika Banjar merupakan hasil asimilasi berbagai etnis dan bangsa, Bakumpai terbentuk dari unsur-unsur Dayak, sehingga lebih tepat disebut etno-religius hibrida. Identitas Bakumpai bersifat akulturatif, dan dapat dijelaskan melalui narasi “Third Space” Homi K. Bhabha—yakni ruang antarbudaya di mana makna lama terganggu dan makna baru tercipta (Bhabha 1994, hlm. 37). Dalam konteks ini, identitas Bakumpai mencerminkan keberhasilan mengelola perjumpaan budaya menjadi ruang hidup yang lentur, adaptif, dan historis.
Namun, untuk memahami Bakumpai, tidak cukup membaca Bab V dan VI saja, karena orang Bakumpai hadir di sepanjang Sungai Barito, dan menjadi aktor penting dalam Perang Banjar, seperti Wangkang, Gusti Matali (pihak Antasari), dan Rangga Niti (pihak Belanda).
Di hulu Marabahan terdapat Mangkatip. Bahasan soal Mangkatip masih menjadi bagian dari Bab VI. Dayak Mangkatip merupakan bagian dari rumpun Dayak Ngaju, satu rumpun dengan kelompok Barangas di Bandarmasih dan Bakumpai di Muara Bahan. Mangkatip dipengaruhi oleh budaya Pulau Petak, Bakumpai, dan Maanyan.
Pada tahun 1857, kepala kampung Mangkatip adalah seorang yang tergolong terpelajar untuk zamannya, karena telah bisa membaca dan menulis dalam aksara Melayu maupun Arab, serta telah berlayar ke Jawa untuk berdagang. Masyarakat Mangkatip pun mulai berpakaian seperti orang Bandar, sehingga Bangert menuliskan orang-orang Mangkatip meniru Melayu.



