Kilasan Institut Dayakologi dalam Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih
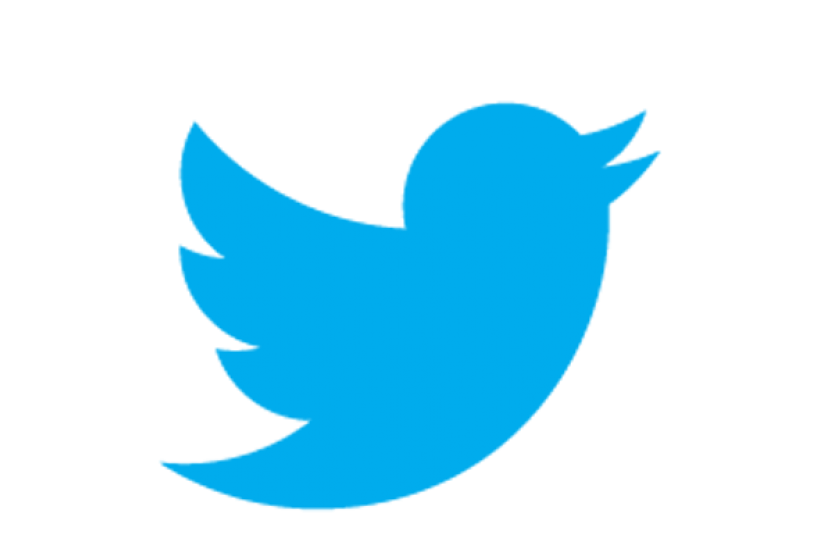
Visi terbaru yang diterapkan oleh GPPK adalah “Masyarakat ‘Dayak’ dan Masyarakat Tertindas pada Umumnya, Mampu Menentukan dan Mengelola Kehidupan dalam Kebersamaan dengan Semangat Cinta Kasih, sehingga Mandiri secara Ekonomi, Bermartabat secara Budaya, dan Berdaulat secara Politik,” dengan misi “Menyelamatkan perjuangan pembebasan suku bangsa Dayak dari dominasi sosial, kultural, ekonomi, dan politik yang menindas.”
Institut Dayakologi
Pada awalnya lembaga ini merupakan sebuah kelompok studi yang memfokuskan diri pada kebudayaan Dayak, terdiri dari kalangan intelektual. Kelompok studi ini menjalan peran sebagai biro penelitian dan pengembangan atau LITBANG Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK) untuk melestarikan, mempromosikan, dan mengembangkan warisan budaya masyarakat Dayak. Lembaga ini terus berkembang sebagai pusat dokumentasi, penelitian, pendidikan, dan advokasi tentang budaya dan pengetahuan tradisional Dayak.
Institut Dayakologi didirikan sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak untuk melestarikan budaya Dayak yang terancam oleh modernisasi, globalisasi, dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada Masyarakat Adat. Berawal dari inisiatif para pendiri aktif dan aktivis awal YKSPK pada akhir 1989 dengan pembentukan Biro Penelitian dan Pengembangan yang kemudian diberi nama Institute of Dayakology Research and Development (IDRD)). Resmi didirikan pada 1991.
Organisasi ini bertujuan mendokumentasikan, meneliti, serta menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional Dayak, meningkatkan kesadaran identitas budaya, dan mendukung advokasi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Pendirian lembaga ini juga merupakan upaya melawan dominasi kekuasaan sentralistik Orde Baru dan kurangnya dokumentasi internal, di mana penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh pihak luar tanpa merepresentasikan perspektif masyarakat Dayak.

Institut Dayakologi didirikan sebagai respons terhadap berbagai ancaman terhadap eksistensi budaya dan identitas masyarakat Dayak. Pendidikan formal berbasis modernisme dan sentralistik cenderung mengikis kebudayaan lokal. Penyebaran agama dominan, baik Islam, Protestan, maupun Katolik mengubah sistem kepercayaan tradisional, bahkan sering kali mengakibatkan migrasi penduduk ke pedalaman atau adopsi budaya baru yang dianggap lebih modern, tapi menghina dan turut mendegaradasi budaya Dayak.
Teknologi media modern mempercepat masuknya pengaruh modernisasi, sementara kebijakan Orde Baru menghancurkan simbol budaya seperti Rumah Panjang dengan dalih kesehatan dan isu politik. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang bias terhadap kepentingan penguasa dan pengusaha mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang menjadi inti dari kebudayaan mereka. Beberapa pengaruh tersebut memang ada yang membawa manfaat positif, tapi di saat yang sama masyarakat Dayak juga dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan kebudayaan mereka di tengah perubahan zaman.
Implementasi
Pencapaian awalnya meliputi penerbitan bulletin 6 bulanan berkembang menjadi Majalah Bulanan Kalimantan Review, pembentukan pusat pelatihan, dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya budaya Dayak melalui penelitian dan kampanye. Institut Dayakologi merealisasikan pandangan dan sikapnya melalui berbagai program, seperti penelitian tradisi lisan (oral tradition) sejak 1992 untuk mendokumentasikan budaya tanpa melanggar hak Masyarakat Adat. Tonggak penting lain yakni pada November 1992, ketika ID (LP3S-IDRD kala itu) menyelenggarakan Seminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Ekspo Budaya Dayak di mana 350 peserta hadir dari dalam dan luar negeri dan lebih dari 6.000 pengunjung.
Penelitian Plants Genetic Resources (PGR) pada tahun 1993, yaitu penelitian mengenai keragaman genetik tumbuhan yang menghasilkan buku Kalimantan; Bumi yang Kaya Makanan (2000). Publikasi melalui Kalimantan Review sejak 1992 menjadi media advokasi dan transformasi Masyarakat Adat yang bertransformasi menjadi KalimantanReview.Com.
Dalam bidang pendidikan, ID memanfaatkan kurikulum 1994 untuk menginisiasi fasilitas pengajaran muatan lokal berbasis budaya Dayak di sekolah dasar. Penelitian etnolinguistik (1997) dilakukan untuk melindungi bahasa Dayak yang terancam punah, diikuti penerbitan buku Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat (2008).
ID juga mempromosikan perdamaian melalui ANPRI bersama dengan CSO di Kalimantan Barat, merespons konflik antaretnis di akhir 1990-an dengan pendekatan multikulturalisme. ID mendesain dan menerbitkan buku ajar Pendidikan Mulok Multikultur untuk kelas VII, VIII dan IX yang direkoemdnasikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
Sementara program pemberdayaan Masyarakat Adat difasilitasi dan diharapkan mampu mendukung kemandirian melalui pendidikan, advokasi, dan pengelolaan ekonomi berbasis komunitas guna membantu masyarakat mempertahankan hak adat serta melindungi sumber daya alam di tengah arus modernisasi.
Kedudukan ID di GPPK
ID salah satu lembaga anggota GPPK dan memainkan peran penting dalam mendukung terwujudnya visi GPPK melalui penelitian, advokasi, dan pelestarian budaya Dayak. Sebagai pusat dokumentasi dan kajian budaya, ID berfungsi sebagai penyusun kebijakan strategis yang mengarahkan gerakan GPPK.
Kontribusi ID terlihat dalam penyelenggaraan seminar, penerbitan jurnal, Kalimantan Review, dan advokasi hak Masyarakat Adat, isu multikulturalisme dan perdamaian serta gerakan lingkungan hidup. ID memperluas jangkauan GPPK secara global dengan menjalin kerja sama internasional dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat dokumentasi budaya Dayak.
Sebagai simbol perjuangan Masyarakat Adat, ID berkomitmen menjaga identitas Dayak sekaligus membangun solidaritas global. ID menunjukkan bahwa gerakan berbasis komunitas dapat menawarkan solusi terhadap tantangan modern sambil melestarikan nilai-nilai tradisional dan resiliensi sosio ekologis yang berkearifan.[*]




