Tanah Dayak Daerah Antropogenik: Tanggapan Terkait Ibu Kota Nusantara (IKN)
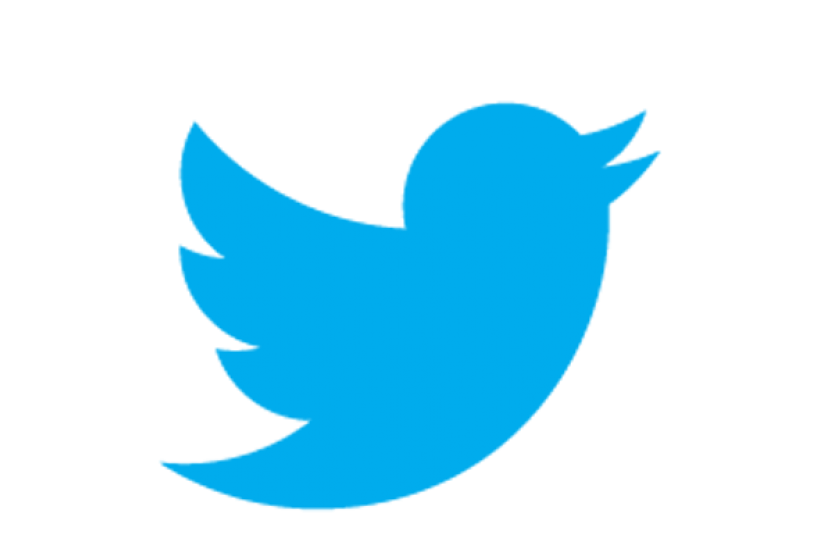
Dalam Draf Naskah Akademi Peraturan soal ‘sejarah masing-masing’ ini sama sekali tidak disinggung. Sedangkan landasan filosofis yang dipakai sama sekali tidak membumi. Seperti pengetahuan tentang masyarakat setempat sangat terbatas, seakan-akan Kalimantan Timur, cq Paser-Panajam itu seperti yang dikatakan oleh kolonialis Belanda dahoeloe adalah terra in cognita (tanah tak bertuan, tanah tak dikenal), etnik yang tidak punya sejarah, sehingga mereka sah datang dan berbuat sesukanya di kampung orang sambil menyebut diri penyelamat, pembawa peradaban. Mudah-mudahan kealpaan ini bukan cerminan dari pola pikir dan mentalitas ‘tuan-tuan penjajah internal’ (internal colonialism).
Sehubungan dengan internal colonialism ini, saya teringat akan kata-kata Bung Karno: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Landasan sosiologi tanpa landasan historis pun nampak asal-asalan. Dangkal. Mengherankan membuat Draf Peraturan tapi pengetahuan tentang daerah yang mau diatur nampak minim. Jika sedikit saja Draf memperhatikan tuntutan-tuntutan dan keresahan masyarakat lokal, cq Dayak, Draf akan tahu apa sesungguhnya yang menjadi “kebutuhan masyarakat di wilayah IKN”. Saya tidak punya cukup ruang untuk menutur sebagian saja dari kebutuhan tersebut. Kalau apa yang saya katakan ini ada benarnya, pertanyaan baru muncul: Di mana pelibatan atau partisipasi masyarakat setempat dalam menyusun Draf sebagai satu misal saja. Partisipasi hanya gelembung sabun mainan anak-anak saja. Atau barangkali masyarakat Dayak karena jumlahnya sedikit menjadi tidak penting bagi Draf?
Pada bagian landasan sosiologis ini juga, Draf ada menyebut tentang “pengetahuan tradisional yang banyak telah hilang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup”. Sayangnya, Draf tidak menguraikan sedikit lebih lanjut tentang mengapa bisa hilang. Siapa yang membuatnya hilang? Hal yang tidak dibicarakan oleh Draf dikemukakan oleh Yunita dengan mengutip Kusumawardani 2022 dalam Zakaria 2023:
“Secara historis, terdapat tiga gelombang eksklusi atas Komunitas Lokal: (1). Lahan komunal menjadi lahan milik Negara — Program Transmigrasi; (2). Pembentukan HPH, HTI, HGU Pertambangan; (3). Konsesi ke Perkebunan Sawit”.
Dengan melihat latarbelakang sejarah seperti ini, kita bisa memahami apa-bagaimana-mengapa keadaan sekarang terjadi. Sebab keadaan hari ini tidak terjadi serta-merta begitu saja. Ketika memahami latarbelakang sejarah hal-ikhwal, kita pun bisa menanganinya dan menghadapinya secara tanggap. Bukan berangkat dari kemauan subyektif belaka. Apalagi jika latarbelakang sejarah itu diusut lebih jauh ke belakang, hubungan suatu hal-ikhwal dengan hal-ikhwal lainnya.
Dalam pertimbangan yuridis, saya tidak melihat adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimasukkan sebagai Undang-Undang rujukan dalam menyusun Draf Peraturan. Padahal pada hemat saya untuk pemberdayaan masyarakat adat di Kalimantan, termasuk pelestarian, revitalisasi dan pengembangan budaya lokal sangat penting. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini Bab XIII mengatur masalah desa adat.
Dalam sejarah Dayak, desa adat mempunyai peran penting dalam memelihara lingkungan dan menyelenggarakan kehidupan yang beradat. Desa adat jauh lebih strategis sifatnya dibandingkan dengan lima skema perhutanan sosial yang pada hemat saya program akal-akalan.
Persoalan besar lain pada Naskah Akademi Draf adalah posisi suku Banjar dan Bugis sebagai sub-suku Dayak Paser. Dengan anggapan begini, maka seperti halnya Dayak, Suku Banjar dan Bugis merupakan Masyarakat (Hukum) Adat juga di Kalimantan Timur. Paralel dengan pandangan ini, di Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, saya pernah mendapatkan komunitas Orang Jawa menyebut dirinya Masyarakat Adat juga, walaupun sejarah asal-usul mereka dari Pulau Jawa dan bertransmigrasi ke Kotawaringin Timur. Dari anggapan bahwa masyarakat suku Banjar dan Bugis yang ada di Tanah Dayak sebagai Masyarakat Adat Kalimantan juga memperlihatkan konsep yang berbeda dengan gagasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jika pandangan ini kemudian diundangkan bukan tidak mungkin ke depan akan menimbulkan suatu keresahan sosial.
Dengan memisahkan antara subyek (kreator), pemangku budaya dari kreasi atau budayanya, apakah Draf sudah menempatkan manusia sebagai pusat, ‘people are the center”?, seperti motto yang digunakan oleh Yunita dalam paparannya? Dengan pemisahan ini, dengan mengutamakan kreasi dibandingkan subyeknya, saya khawatir Draf akan mendorong mentalitas pedagang primer, wujud dari konsep uang sang raja (l’argent roi), yang memandang kreasi adalah komoditas, manusia bukanlah ‘center’ tapi bagian dari komoditas juga.
Hedonisme berujung dengan pereduksian kemanusiaan. Kecurigaan tentang tendens hedonistik pada Draf ini menguat setelah membaca contoh yang diangkat oleh Draf tentang tanaman obat dan upacara pada nasyarakat Paser. Tanaman obat dan ritual adat bisa dijadikan komoditas, misal dalam kegiatan pariwisata.
Dalam hubungan ini juga, pertanyaan saya: Mana yang lebih penting dan utama serta didahulukan, perlindungan terhadap subyek, yaitu Masyarakat Adat, manusianya atau kreasinya? Draf menjawabnya kreasi lebih utama. Bukan subyeknya. Bukan pengampunya. Karena itu Draf tidak bicara apa-apa tentang desa adat, tentang Masyarakat Adat, tentang kepemilikan (Property Right) dan Akses (Access), tentang manusia masyarakiat Dayak. Padahal kreasi tidak akan ada tanpa kreator tanpa subyek atau pengampu.
Apabila pengampunya tergusur, kreasinya pun turut tergusur diganti oleh kreasi dan subyek baru. Kiranya bukan kebetulan suku Banjar dan Bugis oleh Draf disebut sebaagai sub-suku Paser.
Apakah suku Paser sekarang baik-baik saja di bawah bayang-bayang pembangunan IKN? Dalam sebuah laporannya BBC menyebut bahwa” Suku asli Penajam Paser Utara – lokasi Ibu Kota Negara Nusantara – mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri, di tengah kegiatan berkemah Presiden Jokowi dan para gubernur. Mereka menyebut patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara turun temurun.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah NGO memperingatkan potensi konflik yang kemungkinan melibatkan 16.800 orang dari 21 masyarakat adat di sekitar IKN Nusantara” [https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60739196].
Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah sudah memperluas kawasan inti ibu kota dari 5.600 hektare menjadi 6.700 hektare.
“Tapi tidak ada (penggusuran). Kami akan berikan program-program pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Januari 2022 [https://nasional.tempo.co/read/1662331 /pasukan-penjaga-adat-dayak-beri-pesan-soal-proyek-ikn-di-depan-jokowi].
Perbedaan antara keadaan di lapangan dan pernyataan para penyelenggara Negara ini umumnya tidak jarang tidak sejajar. “Jadi, jika kita berbohong kepada pemerintah, itu kejahatan. Jika mereka berbohong kepada kita, itu politik.”, tulis- Bill Murray’ (1950- ), aktor Amerika. Karena itu, “Salah satu alasan orang membenci politik adalah bukan kebenaran menjadi tujuan politisi, tapi pemilihan dan kekuasaan,” ujar – Cal Thomas (1942), kolumnis, pengarang dan komentator Amerika.
Tentang perspektif budaya suku Dayak Paser, Syamsul Rijal, Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Mulawarman, dalam artikelnya berjudul ‘Peluang dan Ancaman, Tentang Budaya Paser di IKN Nusantara’ antara lain menulis: “Berkaca dari masyarakat etnik Betawi yang semakin terpinggirkan sejak Jakarta menjadi kota metropolitan, kini kekhawatiran masyarakat etnik Paser, Kutai, dan Dayak juga harus dihargai terhadap pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Terutama etnik Paser, karena secara langsung etnik Paser berada pada titik pusat pembangunan IKN di Sepaku. Etnik Paser dan budaya Paser merupakan wajah pertama yang dilihat orang yang berkunjung ke Titik Nol IKN Nusantara. Setiap tamu atau pejabat yang datang ke Titik Nol IKN selalu disambut dengan budaya Paser beserta pemangku adat Paser dengan pernak-pernik Pasernya. Ini artinya, di wilayah IKN tersebut lebih cenderung menetapkan budaya Paser sebagai tuan rumah. Selain karena memang dari nama kabupatennya yang sudah menyebutkan Paser.
Sebagai peluang dan ancaman, mampukah budaya dan kebudayaan Paser menerima dan melayani seluruh aktivitas manusia yang berputar di wilayah IKN Nusantara? Atau, sudah siapkah kebudayaan Paser menjadi budaya terdepan yang menampakkan wajah IKN Nusantara?” [https://kaltimpost.jawapos.com/kolom-pembaca/12/08/2022/peluang-dan-ancaman-tentang-budaya-paser-di-ikn-nusantara-1].
Terasa adanya kecemasan pada diri Syamsul Rijal. Apalagi kalaupun kebudayaan Paser ditetapkan sebagai ‘budaya terdepan yang menampakkan wajah IKN Nusantara’, tentu tidak identik dengan lepasnya dari marjinalisasi. Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa Tanah Dayak hari ini tidak lain dari daerah antropogenik. Untuk menghadapinya selain memperkokoh organisasi di semua sektor, boleh jadi yang menjadi kunci adalah memperkuat barisan sumber daya manusia yang berkualitas secara terencana, mengambil jalan minoritas kreatif.
Secara politik-organisasi tata kepemerintahan, pembentukan dan penetapan desa adat mempunyai peran strategis. Sedangkan dari Draf Peraturan yang sedang digodok, agaknya tidak bisa banyak diharapkan. Dia tidak menempatkan manusia sebagai pusat. Barisan orang-orang yang ditinggalkan di belakang pun sedang terbayang jelas seperti orang sedang tenggelam dengan tangan menggapai-gapai mencari pelampung pegangan. Mampukah dan maukah kita menjadi manusia, dan tidak jadi pengemis sert tidak tenggelam di Pulau Antropogenik ini?! ***




