Petak Tahaseng Pambelum (Tanah adalah Nafas Kehidupan): Pidato Kusni Sulang
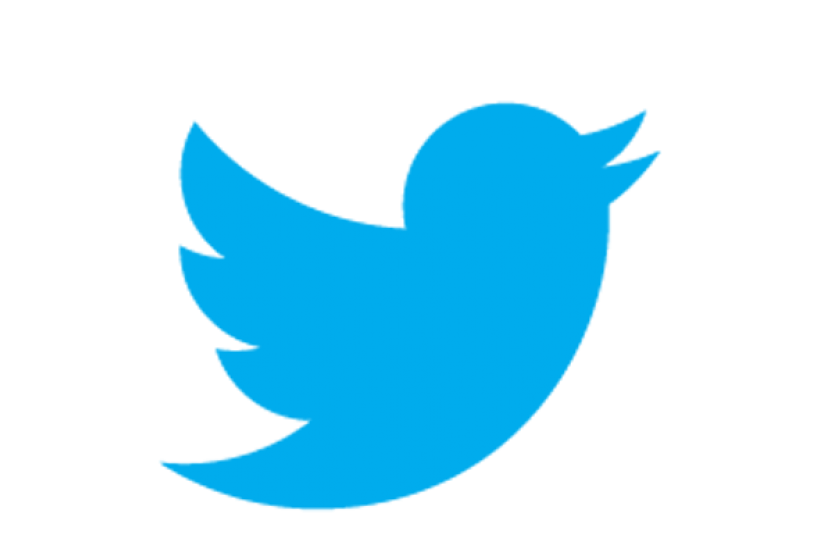
Dari berbagai panitia dan rancangan tersebut, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), yang kala itu dipimpin Haji Zainul Arifin menerimanya dan melahirkan UUPA.
Lahirnya UUPA bermakna besar bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu:
- Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Naskah Asli), yang menyatakan, “Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
- Penjungkirbalikan hukum agraria kolonial dan penemuan hukum agraria nasional yang bersendikan realitas susunan kehidupan rakyatnya.
Pada intinya, UUPA dibentuk dengan meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, dan meletakkan dasar-dasar kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Pembentukan ini dilakukan demi mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam menuju masyarakat adil dan makmur.
Presiden Joko Widodo juga mempunyai Program Reforma Agraria hanya nampaknya berjalan tidak lancar. Tuan tanah baru bukan makin berkurang tapi makin besar, bahkan turut melakukan penyelenggaraan Negara.
Sejarah lahirnya Hari Tani Nasional di atas, memperlihatkan bahwa tanah adalah nafas kehidupan; pétak tahaséng pambélum karena kita tidak bisa bertani di udara.
Hal lain yang patut diingat bahwa monopoli tanah, penguasaan tanah oleh tuan tanah-tuan tanah baru akan menghambat pelaksanaan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Naskah Asli), yang menyatakan, “Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Tanpa tanah, penguasaan monopoli atas tanah akan membuat proses keterpurukan berlanjut, gagasan Manggatang Utus hanya menjadi kata-kata manis pelamis bibir. Dayak akan menjadi jipén kekinian. Inikah pilihan Dayak hari ini?
Sebagai penutup, saya mengajak hadirin merenungi pesan James Brooke (1841-1863) kepada Orang Dayak: “Kumohon dengarkanlah kata-kataku ini dan ingatlah baik-baik: Akan tiba saatnya, ketika aku sudah tidak di sini lagi, orang lain akan datang terus-menerus dengan senyum dan kelemahlembutan, untuk merampas apa yang sesungguhnya hakmu yakni tanah di mana kalian tinggal, sumber penghasilan kalian, dan bahkan makanan yang ada di mulut kalian. Kalian akan kehilangan hak kalian yang turun-temurun, dirampas oleh orang asing dan para spekulan yang pada gilirannya akan menjadi para tuan dan pemilik, sedangkan kalian, hai anak-anak negeri ini, akan disingkirkan dan tidak akan menjadi apapun kecuali menjadi para kuli dan orang buangan di pulau ini.”
Pada tahun 1960-an, pesan dengan isi serupa digaungkan kembali oleh para pendiri Kalimantan Tengah yang pada awalnya dibayangkan sebagai provinsi adat, dalam kata-kata: “Éla sampai témpun pétak batana saré, témpun uyah batawah bélai, témpun kajang bisa puat (Jangan sampai punya tanah beladang di tepi, punya garam hambar di rasa, punya atap basah muatan)”.
Pertanyaan baru yang muncul ketika sudah merenungi pesan-pesan di atas adalah: Apa yang mesti dilakukan untuk menjawab tantangan keadaan demikian yang berlangsung sekarang agar harkat dan martabat manusiawi terjaga? Kita, Dayak mau jadi apa? Mau menjadi budak kekinian (jipén modern) ataukah manusia yang manusiawi?
Orang Dayak-lah yang memastikan jawabannya. Saya hanya menyampaikan salam Uluh Dayak Katingan: Hari! Has Eh! yang bersarikan bahwa Dayak itu Utus Panarung (Keturunan Petarung. Pejuang yang berani dan pandai sampai akhir hayat, bukan tukang kelahi!). Tumbang Oroi, 24 September 2022. (*) (Sumber: Radar Sampit, Minggu 30 Oktober 2022, dan media digital https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2022/11/01/pidato-kusni-sulang-petak-tahaseng-pambelum-tanah-adalah-nafas-kehidupan/, dipublikasikan kembali di kalimantanreview.com atas seizin penulisnya).




