Para Malaikat di Sekitar Rumah Sakit: Preparat Kosong Bapa Uskup
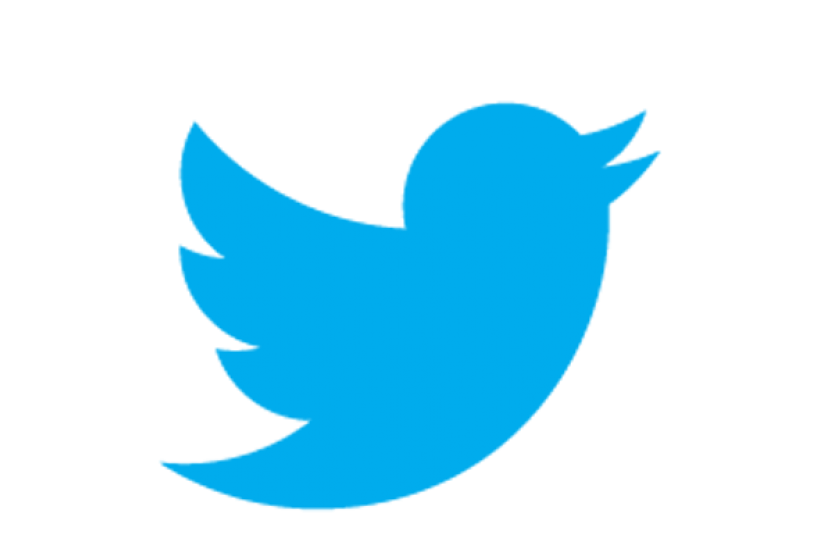
Oleh: Leo Sutrisno – Kolumnis, Dosen Purnabakti Universitas Tanjungpura, Pontianak. Sekarang Tinggal di Yogyakarta.
Dalam keheningan biara yang sejuk, Bapa Uskup Emeritus menerima sepucuk surat singkat dari dr. Justina, seorang dokter spesialis patologi klinik yang ia dampingi secara rohani sejak diagnosis kanker kolorektal stadium lanjut.
Isi surat itu tegas:
“Mgr, saya ingin menyendiri. Mohon sampaikan kepada rekan sejawat, keluarga, dan teman-teman paroki: jangan kunjungi saya. Bahkan jika tujuannya untuk mendoakan saya di depan mata saya sendiri. Saya lelah menjadi objek belas kasihan. Biarkan saya dalam sunyi.”
Bapa Uskup memahami bahwa bagi seorang patolog yang terbiasa melihat sel-sel mati di bawah mikroskop, kini ia harus berhadapan dengan ‘kematian’ di dalam tubuhnya sendiri. Namun, Ia memutuskan untuk tetap datang, bukan untuk melanggar batas, melainkan untuk menjaga batas itu.
Saat tiba di depan pintu rumah dr. Justina, Bapa Uskup tidak mengetuk. Ia hanya duduk di teras, di kursi kayu tua yang jauh dari jendela utama. Ia tidak membawa Alkitab yang terbuka atau rangkaian doa yang lantang. Ia hanya membawa sebuah kotak kecil berisi slide mikroskop kosong yang sudah dibersihkan.
Dr. Jusina, yang melihat dari balik tirai, akhirnya ke luar dengan wajah pucat dan tubuh yang jauh lebih kurus.
“Mgr, bukankah saya sudah bilang? Saya tidak ingin doa-doa yang berisik. Saya tidak ingin dikasihani.”
Bapa Uskup tersenyum tenang, tetap duduk.
“Saya tidak datang untuk mendoakanmu agar sembuh hari ini, Jus. Saya juga tidak datang untuk memberi ceramah tentang mukjizat.” Ia menyerahkan kotak slide kosong itu.
“Sebagai patolog, Anda tahu bahwa seringkali kebenaran hanya ditemukan dalam keheningan ruang gelap dan cahaya mikroskop. Saya di sini hanya untuk menjadi ‘slide kosong’. Engkau, anakku, boleh meletakkan apa pun di atas saya—kemarahan, rasa sakit, atau keinginan untuk tidak bertemu siapa pun—dan saya hanya akan menyangganya tanpa menghakimi.”
Dr. Justina terdiam. Selama ini, orang-orang datang membawa “obat” berupa kata-kata rohani yang justru membuatnya merasa bersalah karena tidak bisa merasa bahagia di tengah sakit.
“Mereka ingin mendoakan saya seolah-olah saya adalah proyek yang harus selesai,” bisik Justina, suaranya parau.
“Maka, biarlah saya menjadi satu-satunya orang yang tidak mendoakanmu dengan kata-kata,” jawab Emeritus ini.
“Saya akan duduk di sini selama satu jam. Kita tidak perlu bicara. Saya akan menjaga pintu depanmu agar tidak ada ‘pendoa’ lain yang masuk mengganggu kesunyianmu. Anggap saja ini penjagaan sakramental atas privasimu.”
Dr. Justina duduk di ambang pintu, berjarak tiga meter dari sang gembala. Selama satu jam, mereka hanya duduk dalam diam. Dr. Jus memandang taman, Bapa Uskup memandang cakrawala. Tidak ada tuntutan untuk menjadi kuat, tidak ada tuntutan untuk bersyukur.
Saat satu jam berlalu, Bapa Uskup berdiri.
“Saya akan kembali minggu depan. Hanya untuk duduk di teras ini. Jika engkau ingin pintu tetap tertutup, saya akan tetap di sini menjaga pintu itu untukmu.”
Untuk pertama kalinya setelah dua bulan, dr. Justina merasa martabatnya sebagai subjek dipulihkan, bukan lagi sebagai objek doa yang dipaksakan. Ia menemukan Tuhan bukan dalam riuh rendah syafaat, melainkan dalam kehadiran seorang gembala tua yang menghormati kemarahannya pada dunia.
“Terima kasih, Mgr,” gumam Justina sebelum masuk kembali.
“Minggu depan… bawa slide yang lain. Saya mungkin punya sesuatu untuk diceritakan.”
Uskup Emeritus berjalan pulang. Ia menyadari bahwa terkadang, pendampingan rohani yang paling suci bukanlah tentang membawa Tuhan kepada seseorang, melainkan membiarkan orang tersebut menemukan Tuhan dalam sunyi yang tidak diganggu.
Dari bibir cakrawala senja, tersirat cahaya lembayung membawa bisikan lirih.
Di balik pintu yang tertutup rapat,




