Para Malaikat di Sekitar Rumah Sakit: Lilin yang Tak Pernah Padam
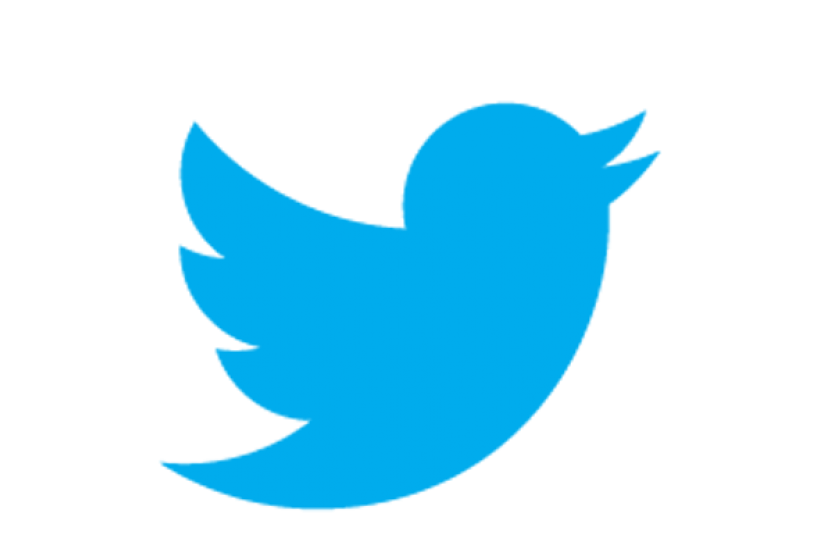
Oleh: Leo Sutrino – Kolumnis, Dosen Purnabakti Universitas Tanjungpura, Pontianak. Sekarang Tinggal di Yogyakarta.
Pagi itu, udara di selasar biara terasa lebih sejuk dari biasanya. Saya sedang merapikan beberapa berkas di kantor yayasan ketika sayup-sayup terdengar suara riuh rendah dari arah gerbang.
Rupanya, sekelompok pria dan wanita dewasa—yang meski sudah berjas dan berpakaian rapi, masih menyisakan binar nakal anak sekolah di mata mereka—telah tiba. Mereka adalah para alumni, teman seangkatanku yang dulu kami belajar dari orang tua itu.
Kedatangan mereka kali ini bukan untuk reuni biasa. Wajah-wajah itu membawa ketulusan yang mendalam. Mereka datang untuk Pak Tua, mantan guru matematika dan Fisika yang kini sedang diuji lewat sakit yang diderita istrinya. Ia sedang berjuang melawan kanker kolorektal stadium lanjut.
Kami berkumpul di ruang tamu sederhana. Salah satu perwakilan alumni, yang kini telah menjadi seorang pengusaha sukses, maju ke depan dengan tangan gemetar. Ia menyerahkan sebuah amplop besar dan sebuah buku kecil berisi daftar nama serta pesan-pesan penyemangat dari teman-teman seangkatannya.
“Suster,” ucapnya lirih, “Dulu orang tua itu mengajarkan kami cara menyelesaikan persamaan yang paling sulit di papan tulis. Sekarang, biarkan kami membantu beliau menyelesaikan persamaan hidupnya yang juga tak kalah rumit”.
“Ini bukan sekadar uang, Suster. Ini adalah tanda kasih kami karena orang tua itu telah membentuk siapa kami hari ini.”
Saya menerima bantuan finansial tersebut dengan hati yang bergetar. Di hadapan saya, saya tidak lagi melihat direktur, dokter, atau manajer. Saya melihat benih-benih kasih, yang dulu ditanamnya, telah tumbuh menjadi pohon rindang dan berbuah manis.
Sakit CA Kolorektal memang berat; biaya pengobatan, kemoterapi, dan perawatan penunjang lainnya seringkali menguras tenaga dan air mata.
Namun, siang itu saya disadarkan kembali bahwa beban seberat apa pun akan terasa lebih ringan jika dipanggul bersama.
“Bantuan ini akan segera saya hantarkan kepada beliau. Siapa di antara kalian yang bersedia menemani”
Mereka menunjuk Carla dan Frans, yang dulu di kelas paling dekat dengannya.
Saat mereka pamit, saya berdiri di depan kapel, memandangi mobil-mobil yang perlahan meninggalkan halaman biara.
Dalam hati saya berbisik. “Terima kasih, Tuhan. Engkau menunjukkan bahwa pengabdian seorang guru adalah lilin yang tak pernah padam. Ia tetap menerangi jalan muridnya, bahkan ketika sang guru sendiri sedang berada dalam kegelapan.”
“Bantuan ini bukan hanya untuk membayar tagihan rumah sakit, tapi untuk mengabarkan bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian”.
Ooo
Dalam catatan harian imaginer pak Tua terbaca lirik nyanyian kasih.




